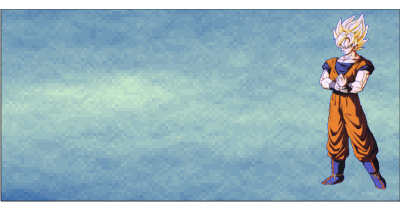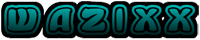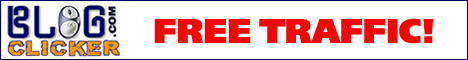Kemenangannya dengan Sultan Hasanuddin pada tahun 1667, membawa tekad yang
lebih besar bagi Belanda untuk menundukkan Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng
Tirtayasa. Strategi ini ditempuh, pertama, karena Banten adalah kekuasaan pemerintah
Islam yang paling dekat dengan Batavia, dan senantiasa bisa mengancam keamanan dan
ketenteraman Belanda di pusat pemerintahannya di Batavia. Kedua, Belanda telah
mengadakan perjanjian damai dengan pemerintahan Mataram di bawah pimpinan Sultan
Amangkurat I, putera Sultan Agung.
Sebelum konfrontasi bersenjata antara Belanda dengan Banten dibicarakan, sebaiknya
diketahui tentang kondisi pemerintahan Islam di bawah pimpinan Sultan Ageng
Tirtayasa. Ia naik tahta kesultanan Banten pada tahun 1651, menggantikan ayahnya
Sultan Abul Fath. Sejak kepemimpinannya, Banten telah naik kembali harkat dan
martabatnya, sehingga kehidupan ekonomi berjalan sangat baik, pelabuhan Banten
ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari Philipina, Jepang, Cina, India, Persia dan
Arab. Islamisasi berjalan dengan sangat mantap, berkat kehadiran seorang ulama besar
dari Makasar yang bernama Syeikh Yusuf. Perannya yang besar, dalam peningkatan
Islamisasi di Banten; menyebabkan ia diambil menjadi menantu oleh Sultan.
Setelah sepuluh tahun memerintah dengan sukses, Sultan mencoba menyiapkan
penggantinya yaitu puteranya Pangeran Ratu untuk memegang kekuasaan di dalam
negeri.
Untuk meningkatkan komunikasi dengan dunia Islam, Sultan pada tahun 1674 telah
mengutus puteranya Pangeran Ratu atau dengan sebutan Sultan Abu Nashr Abdul
Qahhar untuk melawat ke dunia Islam dan sekaligus naik Haji ke Mekah. Perjalanan ini
memakan waktu kurang lebih dua tahun.
Sekembalinya dari perlawatannya, ia diberikan kembali jabatan sebagai Sultan Muda,
yang memerintah dalam negeri Banten, dengan sebutan Sultan Haji. Pergaulannya
dengan para pejabat dan pengusaha Belanda yang mempunyai loji di Banten
mempengaruhi pandangan hidupnya. Apalagi setelah diketahui bahwa adiknya pangeran
Purbaya, yang mempunyai watak dan akhlaq menyerupai ayahnya dan lebih disenangi
oleh para bangsawan Banten, menumbuhkan rasa kecurigaan, jika pengganti ayahnya
itu akan beralih kepada adiknya. Perasaan kecurigaan dan ambisinya yang cepat
menjadi sultan penuh, mendapat tanggapan positif oleh Belanda, yang sehari-harinya
banyak bergaul dengan Sultan Haji. Persekutuan atau lebih tepat persekongkolan antara
Sultan Haji dengan Belanda untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran
Purbaya berjalan dengan rapi.
Peristiwa perompakan atau pembajakan kapal milik Banten yang pulang dari Jawa
Timur oleh kapal-kapal Belanda, menimbulkam amarah Sultan Ageng Tirtayasa,
sehingga ia menyatakan perang kepada Belanda. Kebijaksanaan ini ditentang keras oleh
anaknya Sultan Haji. Bahkan atas bantuan Belanda pada tanggal 1 Maret 1680, Sultan
Haji menurunkan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa dari kesultanan dan mengangkat
dirinya menjadi Sultan Banten.
Tindakan pemecatan Sultan Ageng Tirtayasa menimbulkan reaksi besar dari para
bangsawan Banten di bawah pimpinan Pangeran Purbaya dan para ulama dan rakyat di
bawah pimpinan Syeikh Yusuf. Secara spontan rakyat Banten tidak mengakui
kepemimpinan Sultan Haji di Banten. Dan sebaliknya mereka berkumpul dihadapan
Sultan Ageng Tirtayasa untuk menyatakan kesetiaannya dan bersedia berperang untuk
menurunkan Sultan Haji dan Belanda-Kristen yang menjadi biang keladinya.
Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa telah berhasil menguasai seluruh Banten, kecuali istana
Sultan Haji yang dikelilingi oleh benteng pertahanan yang kuat. Dalam situasi seperti
itu, sesuai dengan persekongkolannya dengan Belanda, Sultan Haji meminta bantuan
pasukan Belanda, yang berpangkalan tidak jauh dari pantai Banten. Dengan seketika itu
pula armada pasukan Belanda-Kristen di bawah pimpinan Laksamana De Saint Martin
pada tanggal 8 Maret 1680 mendarat di Banten. Untuk memperkuat pasukannya,
Belanda mengirimkan lagi satu armadanya di bawah pimpinan Laksamana Tak.
Pada tanggal 7 April 1680 pagi-pagi buta pasukan Sultan Ageng di bawah pimpinannya
langsung, didampingi oleh anaknya pangeran Purbaya dan menantunya Syeikh Yusuf
melakukan serangan umum yang mematikan, terhadap kehidupan Sultan Haji dan
pasukan Belanda. Dalam keadaan yang sangat kritis, Laksamana Saint Martin dan Tak
menyodorkan 'surat perjanjian' kepada Sultan Haji untuk ditanda-tangani, jika bantuan
pasukan Belanda diperlukan oleh Sultan. Untuk mempertahankan hidupnya dan
kekuasaannya, Sultan Haji menanda-tangani surat perjanjian yang sangat merugikan itu
untuk selama-lamanya.
Setelah perjanjian selesai ditanda-tangani, mulailah pertempuran dahsyat antara pasukan
Sultan Ageng Tirtayasa dengan pasukan Belanda meledak. Meriam-meriam besar milik
pasukan Belanda-Kristen dimuntahkan sebanyak-banyaknya ke tengah-tengah pasukan
Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga menimbulkan korban yang banyak sekali, gugur
menjadi syuhada. Kekuatan senjata yang sangat tidak seimbang, mengakibatkan
pasukan Sultan Ageng mengalami kekalahan besar dan akhirnya ia, bersama
pasukannya mengundurkan diri ke istananya di Tirtayasa dekat Pontang.
Tetapi tidak lama kemudian pasukan Belanda mengejarnya dan mengepung kota
tersebut. Atas perintah Sultan Ageng, istana di bumi hanguskan, dan ia bersama
Pangeran Purbaya dan Syeikh Yusuf serta pasukannya mengundurkan diri ke pedalaman
dan membuat markasnya di Lebak (Rangkasbitung). Dari sini Sultan Ageng
melancarkan pertempurannya dengan Belanda selama hampir setahun. Tetapi kemudian
dalam pertempuran itu kerugian senantiasa diderita oleh pasukan sultan, bahkan Syeikh
Yusuf sendiri tertangkap.
Karena sudah tidak ada lagi kekuatan untuk melanjutkan peperangan, akhirnya pada
bulan Maret 1683, Sultan Ageng Tirtayasa menyerah dan ia ditawan oleh Belanda di
Batavia sampai wafatnya pada tahun 1695. Syeikh Yusuf yang ditangkap oleh Belanda
dibuang mula-mula ke Sailan (Ceylon), kemudian ke Afrika Selatan dan di sana ia
wafat, sedangkan Pangeran Purbaya meneruskan perjuangannya dengan bergerilya di
daerah Periangan, tetapi akhirnya juga menyerah.
Selanjutnya, isi perjanjian antara Belanda dengan Sultan Haji, yang ditanda-tangani
pada saat-saat genting itu berisi antara lain:
(a) Semua hamba-sahaya (budak) milik Belanda yang lari melindungi diri ke Banten,
wajib dikembalikan kepada Belanda;
(b) Orang-orang Belanda yang membelot ke Banten dan bekerja untuk kepentingan
Banten, seperti Cordeel, wajib diserahkan kepada Belanda;
(c) Banten tidak boleh turut campur tangan dalam masalah-masalah politik di Cirebon
dan daerah-daerah lain yang berada di bawah wewenang Mataram;
(d) Segala kerugian yang diakibatkan oleh bajak laut dan sabotase oleh Banten terhadap
milik Belanda, wajib ganti rugi dibayar oleh Banten;
(e) Orang-orang asing tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan ekonomi di Banten,
kecuali orang-orang Belanda.
Sultan Haji yang mengangkat dirinya menjadi sultan Banten sejak tanggal 1 Maret 1680
sampai wafatnya tahun 1687, pada hakekatnya telah menjadi bawahan Belanda-Kristen
dan menyerahkan Banten ke bawah telapak jajahan Belanda dengan menumpahkan
darah ayahnya dan saudara-saudaranya sendiri serta rakyat Banten.
Setelah Sultan Haji wafat pada tahun 1687, ia digantikan oleh puteranya dengan gelar
Abu Fadl Muhammad Yahya. Pada tahun 1690, baru tiga tahun ia bertahta, Sultan
Yahya wafat pula dan digantikan oleh adiknya Abu Mahasin Zainal Abidin. Gelar
sultan setelah kekuasaan Sultan Haji pada dasarnya hanya 'sultan boneka Belanda',
sebab yang berkuasa sebenarnya adalah Belanda.
Selanjutnya berdasarkan keputusan pemerintah Belanda di Nederland, pada tahun 1798
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang didirikan sejak tahun 1606
dinyatakan bubar; segala hak-milik dan hutang-hutangnya seluruhnya diambil alih oleh
Pemerintah Belanda. Keputusan itu berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 1799.
Selanjutnya daerah kekuasaan VOC di Indonesia dikuasai langsung oleh pemerintah
Belanda dengan jalan membentuk pemerintahan jajahan dengan nama 'Nederlandsch
Indie' (Hindia Belanda).
Dengan keputusan ini, secara resmi Indonesia merupakan daerah jajahan Belanda.
Untuk mengelola Hindia Belanda ini, maka pada tanggal 28 Januari 1807 Herman
Willem Daendels telah diangkat menjadi Gubernur Jenderal, yang mulai berlaku pada
hari keberangkatannya dari Nederland ke Indonesia yaitu pada tanggal 18 Februari
1807. Ia baru tiba di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1808 dan pada tanggal 15 Januari
1808 timbang-terima dari Gubernur Jenderal Wiese sebagai pejabat tertinggi V OC
terakhir dengan Gubernur Jenderal H.W. Daendels sebagai penguasa tertinggi Hindia
Belanda dilangsungkan di Batavia.
H.W Daendels yang mempunyai tugas utama mengkonsolidir kekuatan militer Hindia
Belanda untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris, maka pekerjaan pertama
adalah membuat pelabuhan armada perang yang berpusat di ujung Kulon dan Merak,
Banten-Jawa Barat. Untuk melaksanakan proyek ini H.W Daendels telah mengerahkan
ribuan tenaga kerja paksa yang terdiri dari rakyat Banten. Kerja paksa (rodi) yang di
luar batas kemanusiaan mengakibatkan tidak kurang 1500 orang telah meninggal dunia.
Melihat nasib rakyat yang malang ini, Sultan Abdul Nasar dan Patih Wargadireja dari
Banten menolak untuk turut serta melanjutkan proyek tersebut dengan jalan tidak lagi
mau mengirimkan tenaga kerja ke sana. Penolakan sultan ini menimbulkan amarah
Gubernur Jenderal, sehingga ia mengirimkan pasukan militer untuk menangkap Patih
Wargadireja; yang dianggap sebagai pimpinan pembangkang, dan memerintahkan
sultan untuk memindahkan istananya ke Anyer serta harus mengirimkan setiap hari
1000 tenaga kerja paksa ke proyek-proyek Daendels.
Pasukan Belanda yang dikirimkan kepada sultan disergap oleh prajurit dan rakyat
Banten, kemudian dibunuh semuanya. Benteng Belanda yang ada di sekitar istana dan
pegawai-pegawai Belanda yang diperbantukan di istana sultan semuanya diserbu dan
dibunuh. Perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa kolonial Belanda
yang bersifat putus asa telah berkembang menjadi huru-hara yang menyulut seluruh
Banten.
Dalam menghadapi gerakan perlawanan Sultan Banten ini, H.W. Daendels telah
mengirimkan pasukan militer yang besar sekali dari Batavia. Ibukota kesultanan Banten
diserang habis-habisan dengan jalan pembunuhan massal dan perampokan harta milik
rakyat Banten yang seluruhnya dilakukan oleh pasukan Belanda. Patih Wargadireja
yang mati tertembak dalam pertempuran itu, jenazahnya dilemparkan ke laut oleh
tentara Belanda. Sultan Abdul Nasar ditangkap dan dibuang ke Ambon dan seluruh
daerah kesultanan dirampas, serta langsung dalam penguasaan Belanda dari Batavia.
Untuk basa-basi putera mahkota diangkat menjadi Sultan Banten dengan gelar Sultan
Muhammad Aliuddin, yang berkuasa atas sebagian kecil saja dari daerah kesultanan
Banten.
Kekejaman dan kebiadaban yang dilakukan oleh pasukan Belanda tidak menyebabkan
matinya ruhul jihad (semangat berjuang) untuk melawan setiap bentuk kezaliman dan
ketidak-adilan yang dilakukan oleh penjajah kafir Kristen. Di bawah pimpinan Pangeran
Ahmad kekuatan perlawanan rakyat disusun kembali dan kali ini bukan hanya rakyat
Banten tetapi juga dengan mengikut sertakan rakyat Lampung. Potensi rakyat besar
yang disertai dengan tekad mati syahid di medan pertempurann perlawanan rakyat
Banten-Lampung ini sulit untuk dapat ditumpas oleh Belanda-Kristen. Berulang kali
pasukan militer Belanda yang dikirimkan dari Batavia untuk menghadapi perlawanan
rakyat Banten-Lampung di bawah pimpinan Pangeran Ahmad senantiasa kandas dan
gagal.
Perlawanan rakyat Banten-Lampung tambah seru, setelah H.W. Daendels membuka
proyek jalan raya dari Anyer sampai Panarukan yang Panjangnya kurang lebih 1000
km, dengan tenaga kerja rodi. Para pekerja yang terdiri dari antara lain rakyat Banten
dalam proyek jalan raya Anyer-Panarukan itu, tak ubahnya bagaikan budak belian yang
pernah dijumpai dalam zaman Romawi kuno. Perlakuan kejam dan sadis oleh pasukan
Belanda-Kristen ini, yang memperpanjang proses perlawanan rakyat Banten-Lampung.
Walau akhirnya, perlawanan Pangeran Ahmad dengan rakyatnya bisa ditumpas oleh
Belanda.
Kekejaman dan kebiadaban penguasa kolonial Belanda yang dilakukan di Indonesia,
selain pandangan hidup yang dimiliki dari ajaran Kristen, yang menganggap umat Islam
adalah keturunan palsu-penyembah syaitan dan manusia setengah monyet, juga karena
dasar untuk mengatur pemerintahannya hanya berorientasi kepada kekuasaan tanpa
hukum. Sebab hukum kolonial zaman VOC berkuasa yang ada hanya di Batavia dengan
nama 'Statuta Betawi', yang berlaku untuk daerah 'Bataviase Ommelanden', dengan
batas-batasnya:
- sebelah barat yaitu sungai Cisadane;
- sebelah utara yaitu teluk Batavia;
- sebelah timur yaitu aungai Citarum;
- belah selatan yaitu samudera Hindia.
Kemudian bagi beberapa daerah para penguasa VOC mencoba mengadakan kodifikasi
dari hukum adat, untuk mengadili penduduk yang tunduk pada hukum adat, misalnya:
(a) Kodifikasi hukum adat Cina yang berlaku bagi orang-orang Cina yang tinggal di
sekitar pusat kekuasaan VOC;
(b) Kodifikasi pepakem Cirebon, dimaksudkan berlaku bagi penduduk bumi putera
(penduduk asli) di Cirebon dan sekitarnya;
(c) Kodifikasi Kitab Hukum Mogharraer yang berlaku bagi penduduk bumi putera di
Semarang dan sekitarnya;
(d) Kodifikasi hukum adat Bone dan Goa, yang berlaku bagi penduduk bumi putera
Bone dan Goa.
Dari fakta-fakta tentang hukum positif yang digambarkan di atas jelas bahwa penguasa
VOC sebagai penguasa kolonial dalam mengatur daerah jajahannya (Indonesia) dari
sejak tahun 1606 sampai dengan tahun 1798 semata-mata berdasarkan 'kekuasaan' dan
bukan berdasarkan hukum.
Begitu pula penguasa Hindia Belanda yang mewarisi Indonesia sebagai daerah jajahan
dari VOC tidak mendasarkan pemerintahannya dengan hukum, tetapi semata-mata
berdasarkan kepentingan kekuasaan. Sebab baru pada tanggal 16 Mei 1846 penguasa
Hindia Belanda melalui Keputusan Raja Belanda di Nederland telah mengeluarkan
pengumuman Pengaturan Baru Tata Hukum di Indonesia, yang dimuat di dalam STB
1847, No. 23.
Pada saat berlakunya 'Tata Hukum Baru' itu maka terhapuslah ketentuan Hukum
Belanda Kuno dan Hukum Romawi; demikian juga segala peraturan dengan nama
'verordeningen, reglementen, publication, ordonansien, instruksien, plakkaten, statuten,
costumen; dan pada umumnya segala peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis, yang di Indonesia mempunyai kekuatan hukum, sepanjang tidak tegas dipertahankan
untuk seluruh Indonesia atau sebagiannya.
Pada pasal 1 dari keputusan Raja Belanda itu, mengatur antara lain tentang:
(a) Ketentuan umum tentang perundang-undangan;
(b) Peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan;
(c) Kitab Hukum Perdata;
(d) Kitab Hukum Dagang.
Sedangkan pengaturan tentang Hukum Pidana termuat dalam pasal 8 dari keputusan raja
tersebut di atas.
Tetapi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dapat
direalisasikan pada tahun 1886, di mana pada waktu itu negeri Belanda telah membuat
Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri yang bernama 'Nederlandsch Wetboek
van Strafrecht'.
Bagi Indonesia yang menjadi daerah jajahan Belanda dengan Hindia Belanda sebagai
penguasanya, waktu itu dibuatkan pula Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna
masing-masing golongan sendiri-sendiri, yaitu:
(a) Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie untuk golongan penduduk Eropa,
ditetapkan dengan Koninklijk Besluit tertanggal 10 Februari 1886; berisi mengenai
tindak kejahatan saja;
(b) Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie untuk golongan penduduk bumi
putera dan timur asing, ditetapkan dengan Ordonansi 6 Mei 1872, berisi hanya
mengenai tindak kejahatan saja;
(c) Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan
dengan Ordonansi tertanggal 15 Juni 1872, yang berisi hanya tentang tindak
pelanggaran saja;
(d) Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan bumi putera dan timur asing,
ditetapkan dengan ordonansi tertanggal 15 Oktober 1915.
Uraian historis tentang hukum positif yang digunakan oleh penguasa kolonial Hindia
Belanda di Indonesia; baru secara formal diatur pada tahun 1846, yang pelaksanaannya
baru bisa dilaksanakan pada tahun 1886. Dengan demikian penguasa Hindia Belanda
yang mengambil-alih kekuasaan VOC pada tahun 1799 dan secara efektif baru berjalan
sejak Januari 1808, dengan Gubernur Jenderal Daendels sebagai penguasa tertingginya,
maka roda pemerintahan kolonial Belanda diatur semata-mata berdasarkan kekuasaan
sampai pada tahun 1886.
Oleh karena itu hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia selama hampir 100
tahun Hindia Belanda berkuasa, senantiasa tergantung pada selera dan keinginan
penguasa kolonial. Nilai benar dan salah, adil dan zalim, baik dan buruk seluruhnya
tergantung kepada pertimbangan akal dan hawa nafsu penguasa kolonial Belanda.
Kriteria mengenai benar dan salah, adil dan zalim, baik dan buruk sepenuhnya kembali
kepada benak dan perut penguasa kolonial Belanda. Dengan kata lain, hampir satu abad
penguasa Hindia Belanda berkuasa di Indonesia (dari 1799-1886) hukum yang berlaku
adalah hukum rimba.
Kekejaman dan kebiadaban yang pola contohnya telah diberikan oleh Gubernur
Jenderal Hindia Belanda H.W. Daendels adalah merupakan pola kekuasaan Hukum
rimba yang diwarisi turun-menurun oleh penguasa kolonial Belanda sampai mereka
angkat kaki dari Indonesia pada tahun 1949 penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada
Republik Indonesia.
Kekejaman dan kebiadaban yang tak terperikan itu, yang melahirkan perlawanan umat
Islam sepanjang masa, dalam periode kekuasaan kolonial Belanda.
Baca Juga Yang Ini
Islam Vs Kristen Di Indonesia